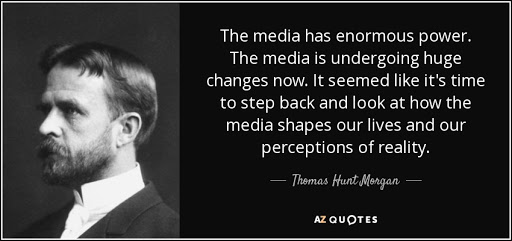" Tumbuhlah menjadi revolusioner yang baik. Belajarlah keras sehingga anda akan menguasai teknik-teknik untuk mengusai alam. Yang terpenting prihatinlah secara mendalam setiap kali ketidakadilan dilakukan terhadap siapapun dibelahan dunia manapun. Ini adalah kualitas terbaik seorang revolusioner" *CHE*
Selasa, 12 November 2019
Kedangkalan Politik dan Lahirnya Angkatan 2019
Rabu, 09 Oktober 2019
Ruang Publik yang Berubah, logika vs fanatik
Tulisan
ini saya tulis pada 17 April 2019, dan secara lebih soft diterbitkan di dalam
kolum Padang Ekspres, silahkan di cek!
https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/126942/Ruang-Publik-yang-Berubah
Silahkan
mengkritisi!!
Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah merubah ruang public tempat interaksi sosial ekonomi politik. Sejak satu dekate belakangan, ruang public atau public sphere yang diperkenalkan Jurgen Habermas berubah menjadi ruang digital atau virtual sphere. Interaksi sosial ekonomi politik tidak saja bersifat langsung diruang public sungguhan, tetapi dilakukan melalui dunia maya yang membuat siapa saja bebas berinteraksi, tanpa sekat, penuh kemudahan. Dunia maya sebagai ruang public baru sangat berbeda dengan ruang public sungguhan. Dunia maya tidak mudah dikontrol, anda dapat tampil secara anonim atau menjadi alter ego-pun tidak ada yang melarang. Ruang diskusi-pun bercampur antara fakta dan fiksi, antara argumentasi dan sentimen. Selain itu, berkembangnya dunia maya sebagai ruang public baru tidak disertai dengan tingkat pemahaman atau literatur pengguna yang baik. Kemudahan akses membuat semua berita ataupun informasi dapat diterima tanpa penyaringan sehingga kejahatan seperti informasi palsu dan kejahatan syber-pun jamak terjadi. Perubahan ruang public ini kemudian dihadapkan dengan sistem politik dan kepemiluan serta masih minimnya regulasi yang mengatur ruang digital.
Sebagaimana Indonesia, sejak pemilu 2009 yang menggunakan sistem pemilu terbuka, membuat suara terbanyak-lah yang akan memperolehan kursi diparlemen. Hal ini berlanjut pada pemilu berikutnya. Nomor urut kandidat yang tidak menentukan keterpilihannya membuat actor-aktor politik berlomba-lomba untuk menciptakan citra politik yang mudah dikenali dan disukai oleh masyarakat. Sosialisasi dan kampanye politik tidak saja berupa strategi darat dengan langsung bertemu dengan konstituen tetapi juga mengunakan strategi udara melalui media sosial dengan mengkreasikan image dan brand kandidat. Disinilah citra kandidat dibuat dengan sebaik-baiknya oleh jasa konsultan politik, jasa konsultan branding atau tim kampanye dan disebarkan melalui buzzer politik yang massif di media sosial. Tak khayal, citra kandidat yang ditampilkan juga terdapat kepalsuan demi naiknya popularitas. Umbaran janji dan citra-citra ini membuat sebahagian masyarakat percaya dengan mudahnya terhadap informasi kandidat tanpa melakukan uji kebenaran. Al hasil, media sosial sebagai ruang public baru ini juga menciptakan fear factory yang terasa betul menebarkan kepalsuan dan ketakutan kepada masyarakat sejak pemilu 2014, berlanjut pada pilkada DKI 2016 dan tentunya pemilu serentak 2019.
Alih-alih mencerdaskan, media sosial dikuasai pasukan cyber yang menebarkan ketakutan dan kepalsuan ke semua orang dan mengganggu kenyamanan kita. Peran malaikat atau hero serta setan atau hantu-pun disasarkan kepada kandidat-kandidat, baik kandidat legislative maupun kandidat presiden dan wakil presiden. Ketakutan dan kepalsuan yang dikonsumsi tanpa kesadaran literature dan regulasi yang ketat ini membuat kematian otak atau cara berpikir. Seolah-olah informasi yang diperoleh sudah benar dan tidak berubah. Dan petakanya, hal ini tidak mengenal status pendidikan dimasyarakat. Kondisi ini lah yang kemudian menciptakan ruang public yang fanatik dan tanpa logika. Media sosial sebagai ruang public baru lebih memainkan emosi para penggunanya. Dengan menyasar emosi pengguna, ruang public baru ini menghidupkan insting-insting purba manusia untuk mempertahankan posisi nyaman dan tidak mau kalah. Saya benar dan anda salah, kandidat saya menang dan kandidat anda kalah. Sebagaimana karakteristik supporter fanatic bola, apabila hasil tidak sesuai dengan insting akan menciptakan kegaduhan dari ruang public maya sampai ruang public sungguhan.
Sehingga, konflik, consensus dan kompromi sebagai bagian dari sikap politik bijak menjadi asing dan sulit diterima. Kisruh atau kegaduhan dalam dunia maya yang sudah berlangsung lama ini seharusnya tidak dibiarkan begitu saja. Terutama dalam kontestasi politik yang menjadi pilar utama dari keberlanjutan demokrasi. Sistem pemilu yang popularistik saat ini seharusnya disertai dengan regulasi yang dapat mengatur keliaran strategi politik yang dipergunakan oleh masing-masing kandidat atau actor-aktor politik. Sebagaiman kita ketahui, peran lembaga konsultan politik dan konsultan branding politik yang memfasilitasi lahirnya buzzer politik atau pasukan cyber tidak diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan. Termasuk Peraturan KPU-pun juga tidak secara signifikan mengatur. Hanya UU ITE yang dapat digunakan untuk menyangsi pelaku yang menebarkan berita palsu terkait dengan kandidat. Alhasil, penyelenggara pemilu dan pengak hukum pemilu yang tersandra dari ketidak siapan negara dalam menghadapi ruang public baru ini. Secara fundamental, mengembalikan sistem pemilu yang tertutup adalah bagian dari solusi guna menghindari supporter politik yang fanatic akibat ruang public baru ini. Tidak ada salahnya mengembalikan sistem pemilu tertutup yang menjadikan partai politik sebagai tempat kaderisasi dan penyaringan bagi kualitas kandidat kembali dihidupkan.
Dengan demikian, kandidat yang terpilih berdasarkan nomor urut dan memiliki Party-Id yang jelas. Masyakat-pun dapat dengan mudah tau bahwa peringkat kualitas kandidat sesuai dengan nomor urutnya. Peran partai politik sebagai jembatan antara masyarakat dan kekuasaan-pun kembali pada tempatnya. Transaksi politik tidak lagi terjadi diruang public seperti saat ini, tapi diperkecil diruang-ruang private. Dengan begitu konsekuensinya berada pada partai politik. Disamping sistem pemilu dan regulasi yang mengatur dunia maya, peran media massa atau jurnalistik adalah hal yang perlu diperbaiki. Keberpihakan media massa akibat kepemilikan saham atau kepemilikan usaha terhadap actor/elite politik tertentu harus dikembalikan sebagaimana fungsinya. Menghadirkan informasi yang kredibilitas, netral dan mengedepankan kode etik jurnalistik adalah hal yang tidak bisa dikompromikan.
Oleh karenanya, masyarakat tidak lari mencari informasi ke dunia maya terutama media sosial yang tidak memiliki prinsip dan etika jurnalistik. Media massa sebagai pilar demokrasi seharusnya tidak menjadi “tongkat yang membawa rebah” dalam proses demokratisasi saat ini dan menjadi penetralisir dari fanatisme yang lahir akibat dunia maya. Terakhir adalah masyarakat yang mau tidak mau dihadapkan dengan ruang public baru ini. Mengedepankan logika atau rasionalitas dengan cara membaca berbagai sumber informasi dan mengedepankan sikap tidak mudah percaya adalah suatu keharusan. Jangan hanya cukup dengan satu sumber informasi dan menganggap informasi tersebut sudah paling benar. Kemudahan akses digital saat ini, sudah seharusnya disertai dengan mengkonsumsi informasi dari berbagai sudut pandang. Dan terpenting, jangan mudah untuk beragumentasi tanpa tau duduk persoalan dan kebenaran dari setiap kejadian. Dulu, mulutmu harimaumu, sekarang dengan ruang public baru ini, jempolmu adalah harimaumu.
Salam Tabik!
Selasa, 16 April 2019
Menghujat Golongan Putih, Yakin?
Restruktur TNI
Politik Gentong Babi
Basyir dan Politik Kepentingan
Media Massa dan Profesionalitasnya
Disamping pentingnya Komisi I DPR RI bersama dengan KPI untuk merevisi UU Penyiaran, tak kalah penting bagi Dewan Pers untuk menegakan UU Pers, terutama bersangkutan dengan penegakan etika jurnalistik dalam pemberitaan. Dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat (2) dikatakan, Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Sebagaimana yang terdapat pada UU Penyiaran sebelumnya, pasal 42 berbunyi, Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukan pentingnya bagi jurnalis sebagai profesi yang diatur dengan kode etiknya.