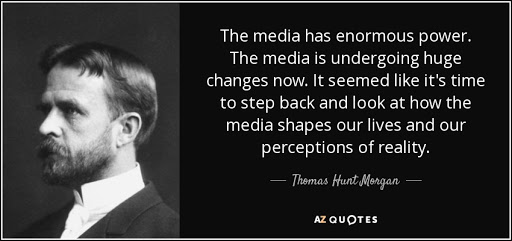Jelang pemilu serentak 17 April 2019, fenomena golput dan kontra terhadap golput menjadi ramai dibicarakan. Tentunya, fenomena golput akan selalu mewarnai setiap diselenggarakannya pemilu. Cukup disayangkannya adalah himbauan untuk tidak golput yang ada saat ini disertai dengan kecaman bahkan juga ancaman.
Sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu tahun 2014, angka golput terus bertambah. Pemilu legislatif 2014 angka golput mencapai 24,89 persen. Dan pada pemilu presiden angka golput mencapai 29,01 persen. Tren tingkat partisipasi-pun dari pemilu ke pemilu di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini bukan menjadi masalah bagi pemilu di Indonesia saja. Bank Dunia pada tahun 2017 telah menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu diberbagai negara demokrasi mengalami tren penurunan sebesar 10 persen dalam kurun waktu 25 tahun belakangan.
Menyadari akan persoalan fenomena golput dan turunnya tingkat partisipasi ini, berbagai upaya dilakukan terutama oleh KPU. Dari menyusun angka target partisipasi pemilu, peningkatan program sosialisasi pemilu, mengaktualisasikan Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh KPU. Bahkan skema pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April ini adalah bagian dari upaya menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Seyogyanya, fenomena golput disetiap pemilu adalah hal lumrah. Mengingat hal ini merupakan perilaku memilih dan hak politik bagi setiap warga negara. Selain itu, secara de jure kehadiran golput tidak bermasalah. Jika pemilu hanya diikuti oleh 30 persen pemilih, secara prosedural hasil pemilu tetap sah. Namun secara de facto, hasil pemilu tersebut layak dipertanyakan karena menyangkut perihal substansi kepemiluan. Meskipun demikian, Golput dan fenomenanya bukan ibarat cendawan setelah musim hujan yang hadir begitu saja.
Mengenal Kriteria Golput
Kehadiran golput dalam pemilu tidak serta merta menandakan tingkat apatis pemilih terhadap politik. Berbagai kalangan menyebutkan Golput sebagai perilaku memilih terdapat dua yaitu golput ideologis dan golput apatis. Benarkah demikian?
Setidaknya terdapat tiga kriteria kehadiran golput dalam pemilu saat ini. Kriteria pertama adalah golput yang sebabkan pada faktor idealisme/ideologis pemilih. Mereka yang termasuk kriteria ini adalah mereka yang tetap datang ke TPS menggunakan hak suaranya, tetapi cendrung merusak kertas suara. Mulai dari mencoblos bukan pada tempatnya sampai pada merusak kertas suara miliknya sendiri. Perilaku memilih yang demikian cendrung dilatar belakangi pada sikap tidak percaya terhadap sistem pemilu, kandidat dan partai politik. Ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu menyangkut pada kinerja penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu dalam menghadirkan pemilu yang berintegritas yang dianggap tidak optimal. Terjadinya praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu yang setiap pemilu tetap terjadi tanpa adanya perubahan, seperti money politik, netralitas aparatur negara dan penegakan sanksi pemilu. Belum lagi menyangkut konflik antar lembaga penyelenggara pemilu yang sering kali membuat pemilih kebinggungan. Selain kinerja penyelenggara pemilu, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu juga menyangkut pada perubahan undang-undang pemilu yang tidak menyelesaikan dan memperbaiki kualitas pemilu. Sejak pemilu 1999 sudah terdapat 4 kali perubahan undang-undang pemilu. Artinya, setiap pemilu dari tahun 2004 diselenggarakan dengan undang-undang yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama dan terus ada.
Ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu ini juga menyangkut pada kandidat dan partai politik. Undang-undang pemilu No 11 tahun 2017 sebagai payung hukum pemilu 2019 ini, menghadirkan sistem pemilu popularitas. Dimana sistem pemilu popularitas ini mengedepankan kandidat yang memiliki popularitas, baik yang diperoleh akibat hubungan sosial maupun yang diperoleh dengan mengakumulasikan modal kapital si-kandidat melalui branding dan marketing. Tidak aneh kemudian, kandidat yang telah melakukan kaderisasi menahun di partai politik kalah saing dengan kandidat popular ini. Dengan sistem pemilu popularitas masing-masing kandidat bebas bersaing, baik sesama kandidat di partai politiknya maupun dengan kandidat dari partai politik lainnya yang satu daerah pemilihan. Nomor urut tidak menjadi acuan, akan tetapi perolehan suaralah yang menentukan. Sehingga, berbagai upaya-pun dihalalkan oleh kandidat-kandidat ini. Baik dari janji-janji politik sampai pada money politik. Kondisi yang demikian-pun tidak menjadi persoalan bagi partai politik, apalagi suara kandidat adalah suara partai politik. Dengan demikian, fungsi kaderisasi di partai politik tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Hiruk pikuk pencitraan dan jasa konsultan politik menjadi langkah strategis.
Keadaan ini bukanlah baru, sejak pemilu 2009 pemilih sudah dihadapkan dengan sistem pemilu yang menghadirkan persaingan sempurna bagi kandidat dan partai politik ini. Akibat dari sistem yang demikian, banyak kemudian kandidat terpilih tidak menepati janji politiknya, berkinerja lemah dan banyak dari mereka-pun tersandra praktik korupsi. Disamping itu, tawaran program kerja atau visi dan misi kandidat bagi pemilih golput ini menjadi acuan fundamental. Isu seperti penegakan hukum dan ham, perlindungan alam dan ekosistem serta perubahan energi fosil ke energi terbaharukan menjadi hal-hal yang sering kali diperhatikan. Seringkali kandidat yang muncul tidak menyuarakan program-program yang subtantif tetapi lebih pada program-program popular dan narasi politik yang bermunculan cendrung ujaran kebencian dan saling olok. Akumulasi dari berbagai persoalan ini-lah yang melahirkan kejenuhan politik bagi pemilih. Oleh karenanya, menjadi golput adalah sebuah pilihan sebagai bentuk protes dan pernyataan sikap tidak percaya terhadap pemilu.
Kriteria kedua adalah mereka yang golput karena apatis terhadap politik. Bagi pemilih golput dengan kriteria ini, menggunakan hak suara dalam pemilu tidak mempengaruhi apapun. Cendrung dari mereka memanfaatkan waktu libur nasional pemilu untuk liburan bersama keluarga dan tetap bekerja. Terutama bagi mereka kelas pekerja non kantor, seperti pedagang, buruh tani dan pabrik. Bagi mereka, politik tidak penting, yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harian keluarga. Selain itu, keyakinan bahwa pemilu tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka menjadi alasan untuk tidak menggunakan hak pilih. Mereka yang golput ini cendrung sangat economic oriented, dan al-hasil malas menggunakan hak pilihnya. Bagi kalangan ilmuan demokrasi, mereka yang golput karena apatis ini cendrung merusak demokrasi.
Dalam konteks Indonesia saat ini, muncul golput kriteria ketiga adalah mereka yang memilih golput dikarenakan faktor administrasi. Hal ini jamak ditemui pada kasus pemilih yang tidak menempati domisili sesuai dengan KTP-nya. Terutama pada pekerja dan mahasiswa/siswa perantauan. Arus perpindahan penduduk tidak selalu disertai dengan kelengkapan berkas administrasinya. Terlebih bagi mereka yang berpindah dikarenakan pekerjaan dan menempuh jenjang pendidikan. Hal ini bersifat sementara dan kadang sering berpindah-pindah kembali. Al hasil, administrasi kepemiluannya-pun terkendala. KPU telah mengupayakan bagi pemilih yang mengalami pindah domisili ini dengan mengajukan formulir pindah pemilih DPTb atau dikenal dengan formulir A5. Mengurus A5 juga dihadapkan dengan rentetan administrasi yang harus disediakan oleh pemilih berupa bukti sudah terdaftar di DPT, copy e-KTP dan KK, surat pengantar RT/RW di tempat kerja/tinggal/surat keterangan kantor/sekolah dan lain-lain untuk membuktikan bahwa benar sedang berdomisili/kerja di lokasi tersebut dan akan mencoblos di lokasi tersebut. Kelengkapan administrasi ini-pun dihadapkan dengan jadwal pengajuan A5 yang sesuai dengan jadwal kerja. Tentu menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi kelas pekerja kantoran ditengah-tengah tugas kerjanya.
Sedangkan bagi mahasiswa, upaya menghadirkan TPS dikampus tempat mereka menempuh pendidikan-pun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pengajuan dari kampus, pertimbangan KPU untuk menghadirkan TPS serta syarat berupa jumlah batas minimal pemilih membuat sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait menghadirkan TPS tambahan di kampus-kampus. Besarnya potensi golput administrasi dikalangan mahasiswa ini dapat dilihat dari potensi golput di Universitas Brawijaya yang diberitakan oleh Kompas 7 februari 2019 lalu. Menurut Andhika Muttaqin, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dari 27.500 mahasiswa UB terdapat 40 persen mahasiswanya merupakan mahasiswa asal Jabodetabek, 10 persennya dari luar Jawa. Ini baru satu universitas, belum lagi universitas lainnya, perguruan tinggi, sekolah dan pesantren atau institusi pendidikan dengan pelajar yang sudah 17 tahun.
Potensi golput admnistrasi tidak datang dari kelas pekerja dan mahasiswa atau pelajar perantauan ini. Mengacu pada indeks kerawan pemilu yang dikeluarkan bawaslu soal golput administrasi ini juga dihadapi oleh pemilih yang mengalami jarak tempuh menuju TPS yang memakan waktu dan biaya. Terkhusus bagi pemilih di daerah-daerah terpencil dan terpelosok. Belum lagi menyoal masyarakat adat yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT. al hasil mereka-mereka yang mengalami persoalan administrasi ini secara tidak langsung terpaksa untuk tidak memilih.
Selain tiga kriteria golput di atas, perlu menjadi perhatian adalah mereka yang telah menggunakan hak pilih akan tetapi suara mereka tidak berguna atau hangus. Hal ini dikarenakan sistem pemilu dengan adanya parliament threshold 4 persen dimana partai politik yang tidak mencapai parliament threshold 4 persen dinyatakan tidak lolos ke senayan. Sehingga suara mereka yang memilih partai tersebut hangus, walau demikian suara mereka masih digunakan untuk partai politik di DPRD Kota/Kabupaten. Dengan sistem Parliament threshold ini, pengguna hak suara tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menempatkan kandidat dan partai politiknya di DPR RI. Terutama bagi mereka pemilih minoritas ini. Dengan demikian, adanya PP 4 persen menandakan sistem pemilu masih sangat ekslusif dan tidak mempertimbangan suara-suara dari pemilih untuk partai-partai kecil. Secara de jure tentu tidak bermasalah, tetapi kembali secara de facto mereka ibarat pemilih yang tidak terwakilkan suaranya diparlemen.
Dengan demikian, golput bukan menyoal apatis semata, tetapi mereka menyangkut pada persoalan ketidakpercayaan pada sistem, kandidat dan partai politik serta juga paksaan administrasi yang membuat mereka memilih untuk golput. Bagaimana-pun, mengacu pada UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 23 ayat 1 telah disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Mereka yang memilih golput tidak perlu dihujat dan dikecam, karena yang mereka butuhkan adalah pembaharuan, substansi, keadilan dan rasa tolerir. Dengan kondisi ini, bukankah kehadiran negara dan pelembagaan partai politik menjadi hal yang krusial agar suara-suara pemilih ini berharga dan bermakna? Atau kita akan selalu berkutat dengan pemilu prosedural tanpa memikirkan substansial dari pemilu itu sendirinya?